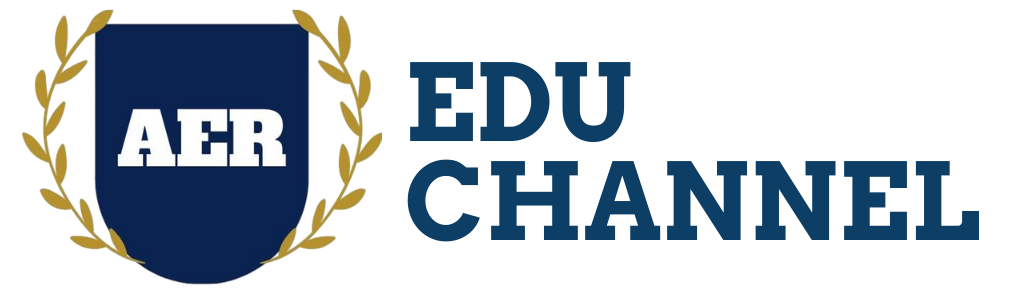Baru-baru ini dunia dikejutkan oleh kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif sebesar 19% terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Keputusan ini mencuat setelah hasil negosiasi bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS, Donald Trump, dalam pertemuan diplomatik yang sarat kepentingan strategis.
Kebijakan tarif ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa langkah Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan proteksionis yang kembali menguat, sementara yang lain melihatnya sebagai hasil kompromi politik yang rumit—sebuah “harga” yang harus dibayar dalam konteks hubungan dagang global.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, kebijakan ini menyimpan makna strategis yang lebih luas. Dalam konteks geopolitik dan hubungan internasional, kebijakan seperti ini bukan hanya soal angka dan persentase, tetapi juga soal posisi tawar, kekuatan nasional, dan kesiapan menghadapi tekanan global.
Di sinilah relevansi pepatah Latin “Si vis pacem, para bellum”—Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang—menjadi sangat terasa.
Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi besar tidak bisa hanya mengandalkan diplomasi lunak dan kerjasama ekonomi semata. Di tengah kompetisi global yang makin keras, daya saing nasional harus diperkuat: dari industri, pertahanan, riset, hingga kebijakan luar negeri yang cermat dan berani.
Pemberlakuan tarif 19% dari AS hendaknya menjadi wake-up call bagi Indonesia untuk tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam membangun kemandirian ekonomi. Presiden Prabowo yang dikenal dengan latar belakang militer kemungkinan besar memahami betul filosofi “Si vis pacem, para bellum” dalam konteks yang lebih luas: damai bukan hadiah, tapi hasil dari kekuatan dan kesiapan menghadapi tantangan.
Jika Indonesia ingin dihormati di panggung global, maka negara ini harus bersiap bukan hanya dengan retorika, tapi dengan strategi. Kekuatan ekonomi nasional harus diperkuat, sektor industri dan ekspor perlu ditingkatkan nilai tambahnya, serta lobi dan diplomasi internasional harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Tarif 19% mungkin terasa pahit dalam jangka pendek. Tapi jika dijadikan momentum untuk membenahi fondasi ekonomi nasional, justru bisa menjadi peluang emas menuju kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
Sebagaimana pesan dalam pepatah kuno: damai hanya mungkin bila kita cukup kuat untuk mempertahankannya.